Tiongkok mendapat pujian dunia atas proyek ambisius penghijauan Gurun Gobi nan sukses menurunkan laju penggurunan sebesar 3,3 juta hektare dalam dua dasawarsa terakhir. Namun pada saat nan sama, perusahaan-perusahaan Tiongkok justru memperluas operasi tperiode di area tropis, termasuk Indonesia.
Di Sulawesi, proyek smelter dan pertambangan nikel menyebabkan deforestasi lebih dari 10.000 hektare rimba sejak 2015. Raja Ampat pun tak luput: eksplorasi nikel menakut-nakuti ekosistem nan merupbakal salah satu pusat keanekaragkondusif hayati laut dunia. Padahal, Raja Ampat bukan hanya rumah bagi lebih dari 1.400 jenis ikan dan 600 jenis terumbu karang, tetapi juga menjadi tumpuan hidup organisasi budaya nan telah menjaga wilayah ini secara turun-temurun.
Protes dari masyarakat budaya Beser dan laporan WALHI Papua Barat menunjukkan bahwa ekspansi industri ekstraktif di area ini mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), dan berisiko merusak tatanan ekologis nan telah lama terjaga.
Fenomena ini bukan hanya terjadi lantaran Tiongkok. Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat pun menjalankan praktik serupa. Jepang, misalnya, tetap mendanai lebih dari 30 proyek PLTU berpatokan batu bara di Asia Tenggara meskipun menyatakan menjalankan transisi hijau di dalam negerinya.
Uni Eropa memberlakukan patokan ketat atas deforestasi, tetapi terus mengimpor produk dari sawit dan kedelai nan ditanam di area nan telah mengalami konversi hutan. Amerika Serikat, meskipun menjadi pemimpin dalam retorika dekarbonisasi, tetap mengandalkan pasokan kobalt dari Republik Demokratik Kongo, di mana lebih dari 40 ribu anak bekerja dalam kondisi berancaman di tambang-tperiode kecil.
Kebutuhan daya bersih dunia justru mendorong peningkatan pemanfaatan mineral strategis di negara-negara berkembang. Indonesia memasok sekitar 30% nikel dunia, Argentina dan Bolivia menyumbang lebih dari 60% litium global, dan 70% kobalt berasal dari Afrika Tengah. Namun, laporan dari Global Witness dan Human Rights Watch menunjukkan bahwa proyek-proyek ini sering tidak melibatkan masyarakat lokal secara adil, menimbulkan bentrok lahan, dan merusak sumber daya air.
Ini adalah corak baru dari kolonialisme ekologis: ketika negara maju mempertahankan kelestarian lingkungannya sendiri sembari mengekspor beban ekologis ke selatan global. Jika pada masa lampau kekuasaan dibangun lewat penaklukan dan perbudakan, sekarang melalui skema investasi, pinjaman, dan proyek-proyek prasarana besar nan berpihak pada korporasi.
Kolonialisme belum benar-betul berakhir—ia hanya berganti wajah. Kini dia datang dalam kebijbakal dagang, konsesi sumber daya, dan perjanjian multinasional nan tidak transparan. Dunia belum bergerak ke arah nan lebih setara; sebaliknya, krisis suasana dan krisis daya justru memperdalam ketimpangan struktural antara negara maju dan berkembang. Ketika negara-negara Utara sibuk menurunkan emisi karbonnya, negara-negara Selatan kudu menanggung akibat dari ekstrtindakan dan pencemaran demi memenuhi kebutuhan industri global.
Dalam konteks ini, kita memerlukan visi penataan ulang ekologi global—suatu tatanan nan menempatkan hak-hak bumi dan kewenangan masyarakat lokal sebagai prinsip utama, bukan sekadar akibat sampingan. Salah satu pendekatan inspiratif datang dari filosofi Buen Vivir di Amerika Latin, nan menekankan harmoni antara manusia dan alam serta pengakuan atas hak-hak kosmos.
Sejalan dengan itu, Naomi Klein dalam bukunya This Changes Everything menegaskan bahwa “What the climate needs to avoid collapse is a contraction in humanity's use of resources. What our economic model demands to avoid collapse is unfettered expansion. Only one of these sets of rules can be changed.”
Hari Menentang Penggurunan dan Kekeringan pada 17 Juni semestinya jadi momentum untuk memandang kembali akar-akar struktural dari degradasi lahan. Gurun bukan hanya hasil alam, tapi juga hasil kebijbakal nan tak adil. Pemgedung nan tak berpijak pada ekologi dan kewenangan masyarakat lokal bakal selalu menciptbakal “gurun sosial”—ruang hidup nan hilang, bunyi nan dibungkam, dan masa depan nan rapuh.
Transisi daya memang niscaya. Namun adilkah jika nan menikmati mobil listrik di kota-kota Eropa dan Asia Timur, sementara nan menanggung polusi dan kehilangan tanah adalah masyarakat budaya di pedalkondusif Indonesia dan Afrika?
Kita butuh model pemgedung nan lebih adil: nan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keseimbangan ekologi dan sosial. Jika tidak, hijau hanya bakal jadi label, dan kolonialisme bakal terus bersambung dalam bentuk nan lebih rapi namun tetap merusak.
Segimana dikatbakal oleh Vandana Shiva, fisikawan dan ekolog asal India: “The ecological crisis is a political crisis. The solutions must be democratic and rooted in justice—justice for the Earth and justice for people.”
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan lingkungan bukan hanya urusan teknokratis alias ilmiah, tetapi juga perjuangan politik untuk keadilan. Masyarakat dunia tidak cukup hanya menanam pohon di negerinya sendiri; mereka juga kudu bertanggung jawab atas jejak ekologis nan ditinggalkan di negeri orang.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim alias sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.

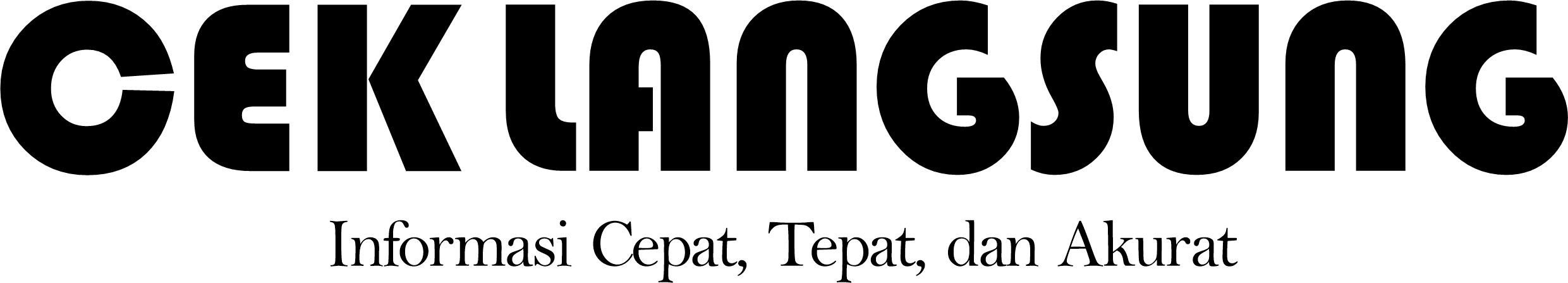 1 bulan yang lalu
1 bulan yang lalu


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5264558/original/080186900_1750855617-WhatsApp_Image_2025-06-25_at_19.02.38_0bd5f825.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5258280/original/065833800_1750349480-WhatsApp_Image_2025-06-19_at_19.49.10.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4138918/original/000594700_1661744726-Bandar_I_Gusti_Ngurah_Rai.jpg)










 English (US) ·
English (US) ·  Indonesian (ID) ·
Indonesian (ID) ·